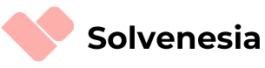Penulis: Syahri Maghfirohtika
Editor: Triana Rahmawati
“Gila” adalah kata yang sering kali dilemparkan dengan enteng, namun dampaknya menusuk dalam bagi mereka yang mengalaminya. Stigma sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Orang Dalam Masalah Kejiwaan (ODMK) tidak lahir dari ruang hampa, melainkan dibentuk dan diperkuat melalui pola interaksi sosial yang berlangsung setiap hari. Seperti yang diungkapkan oleh Goffman (1963), stigma bukan sekadar atribut yang melekat pada individu, tetapi merupakan konstruksi sosial yang lahir dari relasi antar manusia, ketika perbedaan dipandang sebagai penyimpangan yang layak dihindari. Dalam konteks ini, interaksi antara ODGJ/ODMK dan masyarakat sering kali diwarnai oleh ketakutan, prasangka, dan penolakan ditandai dengan jarak emosional, pengucilan, hingga pelabelan negatif seperti “berbahaya” atau “tidak waras.” Tak jarang, pola-pola interaksi ini justru memperkuat isolasi sosial yang sebelumnya telah dialami, menjadikan lingkungan sosial sebagai ladang subur bagi stigma untuk tumbuh dan berkembang.
Namun, tidak semua interaksi melahirkan luka. Di tengah kuatnya stereotip, muncul pula dinamika yang lebih inklusif. Komunitas-komunitas yang telah teredukasi dan memiliki pengalaman langsung dengan pemulihan gangguan jiwa mulai membangun pola interaksi yang suportif dan manusiawi. Keluarga yang dahulu merasa malu, kini menjadi jembatan penting bagi proses reintegrasi sosial ODGJ dengan mengajak mereka kembali dalam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ruang-ruang aman seperti komunitas rehabilitasi, kegiatan seni, atau forum diskusi kesehatan mental menjadi medium penting untuk membangun rasa percaya dan keberdayaan. Di sinilah interaksi berubah wajah: bukan lagi sebagai instrumen pelabelan, melainkan sebagai sarana pemulihan dan pemberdayaan.

Dengan demikian, interaksi sosial memiliki dua wajah: bisa menjadi sumber luka, tetapi juga bisa menjadi jalan pemulihan. Memahami bahwa stigma adalah hasil dari konstruksi sosial, maka solusi terhadapnya pun harus datang dari transformasi cara kita berinteraksi. Ketika masyarakat mulai membuka ruang empati dan menghapus batas-batas stigma, maka saat itulah perubahan yang sejati bermula dari ketakutan menjadi penerimaan, dari pengucilan menjadi pengakuan, dari stigma menjadi solidaritas.
Referensi:
Martiny, S. E., Josten, J., & Renger, D. (2024). Too different to be equal: Lack of public respect is associated with reduced self-respect for stigmatized individuals. Scandinavian Journal of Psychology, 65(2), 304–310.
Thornicroft, G., Rose, D., Kassam, A., & Sartorius, N. (2007). Stigma: Ignorance, prejudice or discrimination? The British Journal of Psychiatry, 190(3), 281–283.