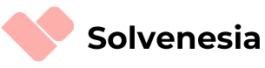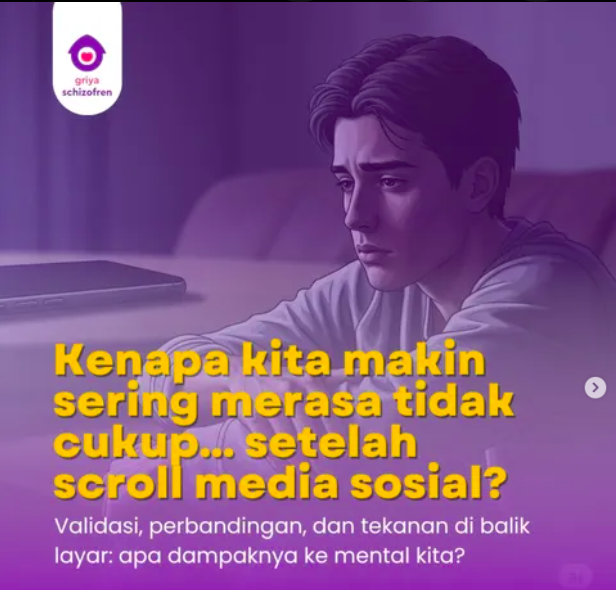Penulis: Syahri Maghfirohtika
Editor: Triana Rahmawati
Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter bukan sekadar ruang berbagi informasi, tetapi juga arena pembentukan citra diri. Di sinilah banyak orang, tanpa sadar, menjadikan validasi digital seperti jumlah “like”, komentar, dan followers sebagai tolok ukur harga diri. Fenomena ini mendorong munculnya tekanan sosial baru: kebutuhan untuk tampil sempurna, diterima, dan disukai secara daring. Ketika ekspektasi tidak terpenuhi, perasaan tidak cukup, cemas, hingga depresi pun mulai muncul. Masalah ini tak hanya berdimensi psikologis, tetapi juga sosial dan struktural.
Secara sosiologis, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep Looking-Glass Self dari Charles Horton Cooley, yang menyatakan bahwa identitas diri terbentuk dari cerminan reaksi orang lain terhadap kita. Ketika reaksi itu datang dari media sosial yang serba kuratif dan manipulatif, maka citra diri yang terbentuk pun rentan tidak otentik. Ditambah lagi dengan Social Comparison Theory dari Festinger, yang menjelaskan bagaimana individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Di media sosial, perbandingan ini menjadi semakin intensif karena semua orang berlomba menampilkan versi terbaik hidup mereka. Akibatnya, banyak pengguna mengalami tekanan sosial, kecemasan, dan ketidakpuasan terhadap diri sendiri.
Berbagai studi telah menguatkan temuan ini. Penelitian oleh Putri dan Atmoko (2024) menunjukkan bahwa kecanduan media sosial berdampak pada kelelahan mental, stres, dan gangguan tidur. Studi lain oleh Azaria dkk. (2024) menemukan bahwa banyak remaja di Yogyakarta secara sadar mengurangi penggunaan Instagram karena merasa cemas dan tidak aman secara sosial. Literature review oleh Afsari dkk. (2023) juga menyimpulkan bahwa intensitas penggunaan media sosial berhubungan signifikan dengan tingkat kecemasan sosial di kalangan remaja. Bahkan, menurut Sahputra dkk., kebutuhan untuk membuka diri secara daring (self-disclosure) justru sering memperburuk kecemasan, apalagi jika tanggapan yang diterima tidak sesuai harapan.
Kondisi ini juga berkaitan dengan struktur kekuasaan dalam dunia digital. Media sosial mendorong budaya “masyarakat tontonan”, sebagaimana dijelaskan oleh Guy Debord, di mana kehidupan manusia lebih ditujukan untuk dilihat dan dinilai daripada dijalani secara otentik. Algoritma media sosial pun bekerja sebagai mesin pembentuk realitas, menentukan konten mana yang dianggap layak, viral, atau tidak. Ketika kesehatan mental menjadi korban dari sistem digital yang menuntut keterlibatan konstan, maka permasalahan ini tidak bisa lagi dipandang sebagai masalah personal semata.
Oleh karena itu, isu kesehatan mental di era media sosial harus disikapi secara kolektif. Literasi digital yang lebih kritis perlu diperkuat, terutama pada remaja dan mahasiswa. Layanan konseling harus lebih mudah diakses dan tidak lagi distigmatisasi. Selain itu, tanggung jawab sosial juga perlu dibebankan pada platform media sosial, agar mereka tidak hanya mengejar keterlibatan (engagement), tetapi juga ikut melindungi kesejahteraan mental para penggunanya. Kesehatan mental adalah hak, bukan kemewahan yang hanya dimiliki oleh mereka yang mampu dan paham.
Referensi:
Putri, A. B., & Atmoko, W. B. (2024). Dampak Kecanduan Media Sosial terhadap Kesehatan Mental. Jurnal Humaniora dan Riset.
Azaria, A. S., dkk. (2024). Instagram dan Kesehatan Mental Generasi Z. Jurnal CANTRIK UII.
Afsari, I. A., dkk. (2023). Relationship Use of Social Media to Anxiety in Adolescents in Indonesia. CMHP Journal.
Sahputra, D., dkk. (2023). Munculnya Kecemasan Sosial sebagai Masalah Kesehatan Mental pada Pengguna Media Sosial. Jurnal Caraka.